Text
Menapak jejak Amien Rais : persembahan seorang putri untuk ayah tercinta
(Dikutip dari Bab 3: Menembus Batas, hal: 133)
* * *
Malam itu, sebuah telepon berdering untuk bapak. Telepon penting nan genting. Bapak yang saat itu berada dalam perjalanan, diminta segera datang ke rumah Pak Habibie. Hampir semua pimpinan partai politik dan pimpinan fraksi telah berada disana. Termasuk diantaranya adalah Akbar Tanjung, Ginanjar Kartasasmita, Hamzah Haz dan Yusril Ihza Mahendra. Selain para politisi dari Poros Tengah dan Golkar, ada juga perwira tinggi TNI. Setiba di kediaman Habibie, bapak langsung didaulat. Jendral Wiranto spontan menepukkan tangannya di bahu bapak.
“Bismillah Pak Amien, TNI ada dibelakang anda, jika Pak Amien bersedia dicalonkan menjadi presiden”, demikan kata kata Jendral Wiranto, yang saat itu merupakan panglima tinggi ABRI. Sebuah daulat yang diamini oleh semua orang yang berada dalam ruangan tersebut.
Bapak berkisah padaku, ia sungguh berada dalam sebuah dilemma. Menjadi Presiden. Memegang tampuk kepemimpinan paling tinggi di negara ini. Menjadi pengambil kebijakan akhir dalam setiap urusan pemerintah dan rakyatnya.
Jawaban bapak atas pertanyaan Permadi dalam sebuah seminar pra-reformasi mengiang kembali, “Pak Amien, beranikah Anda menjadi Presiden?” dan bapak menjawab, “Insya Allah Berani’’
Ia berani, karena kata kata itu semula ia maksudkan hanya sebagai wacana ice breaker untuk memecah kebuntuan demokrasi di masa orde baru. Bapak tahu benar, tidak ada celah sedikitpun untuk menjadi presiden saat itu.
Tapi sekarang? Tawaran menjadi Presiden bukanlah wacana, tapi sangat dekat didepan mata. Diusung Golkar, TNI, dan Poros Tengah. Jadi, sangat kuat dukungan di MPR. Perjuangan untuk rakyat secara konkret akan bisa segera terlaksana, seperti yang dicita-citakan bapak.
Ketika bapak menceritakan apa yang terjadi pada malam itu, aku membayangkan seperti menjadi seseorang yang melihat harta karun berlimpah tak bertuan ada didepan mata. Aku pasti akan mengambilnya. Tapi bapak, tidak.
Bapak berkonsultasi dulu dengan ibunda tercintanya tentang tawaran ini, namun nenekku kemudian memberi nasehat, “Mien, tanggung jawabmu di MPR baru saja dimulai. Kamu telah disumpah menjadi ketua MPR untuk masa bakti 5 tahun. Jangan berbelok di tikungan. Itu tidak bagus. Aku tidak setuju”.
Bapak dengan halus menampik tawaran Habibie, Wiranto, dan segenap politisi yang berkumpul di rumah Habibie malam itu. Tampuk kepemimpinan Indonesia akhirnya diterima oleh Abdurrahman Wahid sebagai calon dari Golkar, Poros Tengah, dan TNI, menyisihkan Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan Presiden di Sidang Umum MPR 1999.
* * *
Nenekku, ibunda tercinta bapak adalah figur yang begitu sentral dalam kehidupan bapak. Sosok ibu sejati bagi anak-anak dan lingkungannya. Tak heran, bila nenek pernah mendapat predikat Ibu Teladan se eks-karesidenan Solo. Sebelum bapak mengambil keputusan keputusan penting, ia selalu meminta pendapat dan restu terlebih dahulu dari ibundanya. Termasuk saran penting dari ibundanya untuk menolak tawaran menjadi calon presiden pengganti Habibie yang didukung Golkar, TNI dan poros tengah. Bagi bapak, restu seorang ibu sangat powerful, meski terkadang harus ditelan dengan kepahitan. Kepahitan karena harus menghadapi amarah massa yang tidak terima dengan gagalnya Megawati menjadi presiden. Mereka merusak dan membakar rumah nenek, ibunda bapak.
Nenek yang sudah renta, harus diungsikan dari kerusuhan massa yang membumi hanguskan kota Solo pada 20 Oktober 1999. Malam sebelum insiden pengrusakan dan pembakaran, kerabat di Solo telah mendengar ancaman dan desas desus bahwa sekelompok massa akan menyerbu ke rumah ibunda Amien Rais di Kepatihan, Solo. Kerabatku segera mengungsikan nenekku ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Solo. Tiada waktu lagi untuk menyelamatkan barang berharga apapun didalam rumah. Suara nenekku yang kebingungan karena tiba tiba harus diungsikan, masih melekat di ingatanku.
‘’Aku meh digowo nengdi?. Aku ora lara kok digowo ning PKU’’
(Aku akan dibawa kemana. Aku kan tidak sakit mengapa dibawa ke PKU?)
Pamanku Abdul Rozaq Rais yang bertugas mengungsikan nenek tak kuasa menahan air matanya. Sambil memapah sang bunda, pamanku itu terpaksa berbohong.
‘’Rumah ini akan direkonstruksi, Bu. Ada bagian yang mau ambruk harus diperbaiki. Nanti selesai rekonstruksi pasti ibu bisa kembali lagi ke rumah’’
Rasanya berkecamuk perasaan pamanku saat itu. Kenyataannya adalah rumah itu bukan akan direkonstruksi menjadi lebih baik, melainkan didestruksi besar besaran pada pagi harinya. Sekelompok orang yang beringas menjebol pintu dan jendela rumah lalu memporak poranda semua isi rumah nenek.
Rumah nenek yang sederhana, tempat bapak dan kelima saudaranya dibesarkan, luluh lantak dalam waktu kurang dari 3 jam. Beberapa bagian ruangan di dalam rumah juga dibakar. Foto kenangan keluarga tak lagi bersisa. Para tetangga yang menyaksikan aksi beringas tersebut hanya bisa diam termangu karena takut pada massa yang membawa parang dan golok. Konsentrasi kepolisian saat itu terpecah pada rusuh massa lainnya di Solo yang menyerang fasilitas publik di kota. Seorang tetangga menyesal mengapa pihak kepolisian tak bisa datang lebih cepat padahal mendapat laporan kejadian tersebut sejak awal.
Salah satu tetangga juga menceritakan bahwa ia mendengar omelan sang anarkis yang menggerutu karena tak menemukan sesuatu yang berharga untuk dijarah.
‘’Sialan. Omahe mak’e Amien ora ana isine apa-apa. Mung radio karo kulkas!’’
(Sialan. Rumah Ibunya Amien tak ada isinya. Cuma radio dan kulkas!)
Orang tersebut berharap bisa menemukan barang berharga seperti perhiasan emas atau uang tunai yang disimpan oleh nenekku. Tentu saja mereka tak berhasil mendapatkan buruan tersebut. Karena nenek memang tak pernah bergelimang harta dan barang mewah didalam rumahnya.
Bapak sangat terpukul, mengapa aksi perusakan dan pembakaran rumah tersebut tak bisa terhindarkan. Ia merasa telah melibatkan ibunya yang telah berumur 80 tahun lebih menjadi korban dari sepak terjang politiknya. Ia tak bisa membayangkan apa yang akan dipikirkan oleh ibunya jika tahu rumahnya diporak-poranda.
Tapi agaknya Tuhan tak mau bapak merasa seperti itu. Allah telah membuat sebuah skenario yang maha agung untuk menyelamatkan nenek dari berita-berita yang membuat hatinya bersedih. Penyelamat itu adalah penyakit Alzheimer yang diderita oleh nenek selama 5 tahun terakhir. Memori nenek sangat pendek dan semakin pendek terhadap segala hal yang baru saja terjadi.
Setiap nenek menjalankan shalat fardhu, setengah jam kemudian ia akan mengulang shalat fardhunya kembali karena merasa belum menunaikan shalat. Sehingga, dalam sehari, ia bisa bersembahyang lebih dari 20 kali.
Persis saat akhirnya ia diberitahu pelan-pelan bahwa rumahnya sebenarnya telah dirusak orang. Ia hanya bersedih beberapa menit saja. Lalu Alzheimer akan membuatnya segera lupa, meninggalkan kesedihannya, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Setiap beberapa jam, nenek kembali bertanya mengapa ia harus berada di PKU Muhammadiyah sementara dirinya merasa tak sakit. Mengapa ia tak boleh pulang ke rumahnya? Lalu jawaban pamanku Rozaq Rais akan selalu sama. ‘’Rumahnya masih direkonstruksi, Bu’’. Beberapa minggu nenek di RS PKU Muhammadiyah, nenek terus menerus bertanya kapan ia bisa segera pulang ke rumahnya. Menanyakan mengapa rekonstruksi rumahnya tak kunjung selesai.
Dua tahun berselang sejak insiden pengrusakan rumah nenek, aku diajak bapak ibu menjenguk nenek di Solo. Kata dokter otak nenekku semakin mengkerut, Alzheimer semakin akut. Akibatnya, nenekku itu tak pernah tidur nyenyak karena selalu merasa belum shalat 5 waktu. Para handai taulan tak bosan mengingatkan bahwa ia telah shalat puluhan kali sehari. Tapi nenek tak percaya. Ia mengatakan ada seseorang di luar jendela rumahnya yang selalu mengingatkannya untuk segera shalat. Padahal, kami semua tak pernah melihat siapa-siapa di luar jendela kamarnya. Saat itulah, kami semua sadar, waktu berpulang nenek telah semakin dekat.
Hari-hari itu, sudah tak ada lagi ingatan yang tersisadidalam benak nenekku selain shalat, shalat, dan shalat. Beberapa hari kemudian, nenek kritis. Ia dilarikan kembali ke RS PKU Muhammadiyah Solo. Sejak 13 September 2001 nenek koma tak sadarkan diri. Ia terbaring lemah di ruangan rumah sakit. Saat itu aku terus berharap agar nenek segera membuka matanya lagi, ’’Ayolah Nek, bangunlah. Tanyakan pada kami disini tentang shalat dan kapan rekonstruksi rumah selesai’’ .
Tapi rupanya Allah berkehendak lain. Ia membuat kami tak kan pernah lagi mendengar pertanyaan nenek tentang shalatnya dan rekonstruksi rumahnya. Jumat 14 September 2001, dua jam menjelang shalat Jumat, nenekku Sudalmiyah Syuhud Rais menghembuskan nafas terakhir.
Innalillahii wa inna ilaihi rooji’uun. Nenekku berpulang kerahmatullah menyusul suami tercintanya yang telah berpulang pada tahun 1985. Semua orang mencium dahi nenek. Bapak, ibu, pamanku, dan seluruh kerabat dekat mencium dan mendoakannya. Bapak yang tak pernah sekalipun aku melihatnya meneteskan air mata, kali ini tak bisa lagi membendung derasnya kesedihan akan kepergian orang yang telah mengandung dan membesarkannya.
Saat giliranku mencium dahinya, aku pejamkan mata dan berdoa sejenak. Lalu aku berbisik lirih di telinganya.
‘’Mbah, rumah Simbah sudah selesai direkonstruksi. Sekarang, Simbah boleh pulang ke rumah untuk selamanya…’’
Ketersediaan
Informasi Detail
- Judul Seri
-
-
- No. Panggil
-
923.2 Han m
- Penerbit
- Jakarta : Esensi., 2010
- Deskripsi Fisik
-
-
- Bahasa
-
Indonesia
- ISBN/ISSN
-
978-979-075-514-7
- Klasifikasi
-
923.2
- Tipe Isi
-
-
- Tipe Media
-
-
- Tipe Pembawa
-
-
- Edisi
-
-
- Subjek
- Info Detail Spesifik
-
-
- Pernyataan Tanggungjawab
-
Hanum Salsabiela Rais
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar
 Karya Umum
Karya Umum  Filsafat
Filsafat  Agama
Agama  Ilmu-ilmu Sosial
Ilmu-ilmu Sosial  Bahasa
Bahasa  Ilmu-ilmu Murni
Ilmu-ilmu Murni 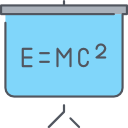 Ilmu-ilmu Terapan
Ilmu-ilmu Terapan 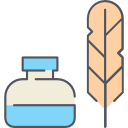 Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 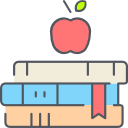 Kesusastraan
Kesusastraan  Geografi dan Sejarah
Geografi dan Sejarah